REBANA: Tentang Pusat, Pinggiran, dan Siapa yang Memiliki Perubahan
- Priyo Utomo Laksono
- 6 days ago
- 3 min read
Updated: 3 days ago

REBANA—begitulah ia disebut. Sebuah nama yang terdengar ringan, hampir seperti bunyi alat musik, padahal ia memikul beban yang berat: harapan tentang masa depan pembangunan Jawa Barat, bahkan mungkin Indonesia.
REBANA adalah singkatan administratif, tentu saja, yang jujur saja terdengar dipaksakan tapi mudah diingat. Ia merujuk pada gugus wilayah di utara dan timur laut Jawa Barat: Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon. Dalam bahasa kebijakan, ini disebut metropolitan baru—sebuah kawasan aglomerasi yang dirancang agar tidak lagi bergantung pada Jakarta dan Bandung sebagai pusat tunggal pertumbuhan.
Namun dalam percakapan yang lebih jujur, REBANA bukan sekadar singkatan. Ia adalah pertanyaan: mungkinkah pembangunan tidak lagi menumpuk di satu titik?
Dan lebih jauh lagi: siapa yang sebenarnya memiliki perubahan itu?
Wilayah ini dihuni hampir sepuluh juta manusia—angka yang, jika dilepaskan dari tabel statistik, sebetulnya berarti sepuluh juta kehidupan sehari-hari: orang berangkat kerja, anak-anak sekolah, sawah yang mengering, bengkel kecil di pinggir jalan, kota-kota kabupaten yang lengang di siang hari. Pemerintah melihatnya sebagai potensi demografis. Warga menjalaninya sebagai realitas.
REBANA dirancang sebagai jawaban atas satu trauma panjang pembangunan nasional: pemusatan. Kita tahu kisah itu—Jakarta yang membesar seperti magnet, menyedot tenaga kerja, modal, dan mimpi; sementara daerah-daerah lain belajar hidup dalam posisi menunggu. REBANA, setidaknya di atas kertas, ingin mematahkan pola itu.
Ia ditopang oleh infrastruktur besar: Pelabuhan Patimban yang membuka pintu logistik, Bandara Kertajati yang diharapkan menjadi simpul udara, jalan tol dan rel yang merapikan arus barang dan manusia. Di sekelilingnya, kawasan industri direncanakan, hunian dibangun, pusat-pusat ekonomi baru diharapkan tumbuh.
Tapi pembangunan tidak pernah hidup hanya dari angka. Ia hidup—atau mati—di tingkat pengalaman manusia.
Esai ini lahir dari permenungan setelah menyimak sebuah diskusi, terutama dengan Budhiana Kartawijaya—wartawan senior, mantan pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, seseorang yang puluhan tahun hidup di persimpangan antara peristiwa, kekuasaan, dan bahasa. Karena latar belakang ini lah saat ini ia diberi tanggung jawab menjadi Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal REBANA. Ia berbincang bersama Indra Hidayat dan Arif Yudi, dan Yuri Alfa Centauri.
Ada satu kalimat Budhiana yang terus menggema bahkan setelah rekaman berhenti:
“Sebuah transformasi akan gagal jika transformasi itu hanya menjadi milik kalangan atas.”
Kalimat itu terdengar sederhana, hampir klise. Tapi justru di situlah daya ketuknya. Ia seperti mengetuk sesuatu yang selama ini kita anggap wajar: bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa benar-benar dimiliki oleh mereka yang paling terdampak olehnya.
Namun perbincangan menyentuh lebih dari soal peta, grafik, atau proyeksi investasi. Ia menyentuh, sadar atau tidak, sesuatu yang lebih rapuh: kepemilikan makna. Tentang siapa yang merasa menjadi bagian dari transformasi itu, dan siapa yang hanya menjadi latar belakangnya.
Dalam diskusi itu, REBANA perlahan bergeser dari sekadar akronim kebijakan menjadi pertanyaan kultural. Apakah wilayah hanyalah ruang kosong yang menunggu diisi modal? Ataukah ia sudah penuh oleh ingatan, kebiasaan, dan cara hidup yang tidak selalu kompatibel dengan bahasa perencanaan?
Indra Hidayat, sebagai pengusaha sekaligus warga Sumedang, menyinggung kegelisahan yang lebih praktis namun tak kalah penting: “Okay akan terjadi seperti itu (pengembangan REBANA, terus saya ngapain)?” Sebuah pertanyaan yang jarang muncul dalam dokumen resmi, tapi selalu muncul di warung kopi dan teras rumah.
Di titik ini, pembicaraan tentang REBANA tidak lagi terasa sebagai diskusi wilayah, melainkan diskusi tentang demokrasi sehari-hari. Tentang jarak antara rencana besar dan pengalaman kecil. Tentang bagaimana pembangunan sering kali hadir sebagai keputusan yang sudah jadi, bukan proses yang bisa dinegosiasikan.
Investasi memang tidak pernah netral. Ia selalu membawa nilai, selera, dan bayangan masa depan tertentu. Maka jika pembangunan hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, kita sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih halus namun fundamental: kebudayaan. Cara orang bekerja, berkumpul, memaknai ruang, bahkan membayangkan diri mereka sendiri di masa depan.
Di sinilah REBANA menjadi menarik sekaligus rawan. Ia bukan sekadar proyek wilayah, melainkan eksperimen sosial berskala besar. Apakah ia akan menjadi ruang hidup yang memungkinkan warga tumbuh sebagai subjek—atau hanya sebagai penonton dari perubahan yang tak mereka rancang?
Esai ini tidak bermaksud memberi jawaban. Ia lebih sebagai pengantar, renungan seorang redaktur yang mendengarkan, mencatat, lalu menyadari bahwa di balik singkatan yang terdengar seperti alat musik itu, ada pertaruhan serius tentang siapa yang boleh ikut memainkan iramanya.
Dan barangkali, pertanyaan terpentingnya bukan lagi: apa itu REBANA?
Melainkan: siapa yang boleh menabuhnya, dan untuk siapa bunyinya ditujukan?
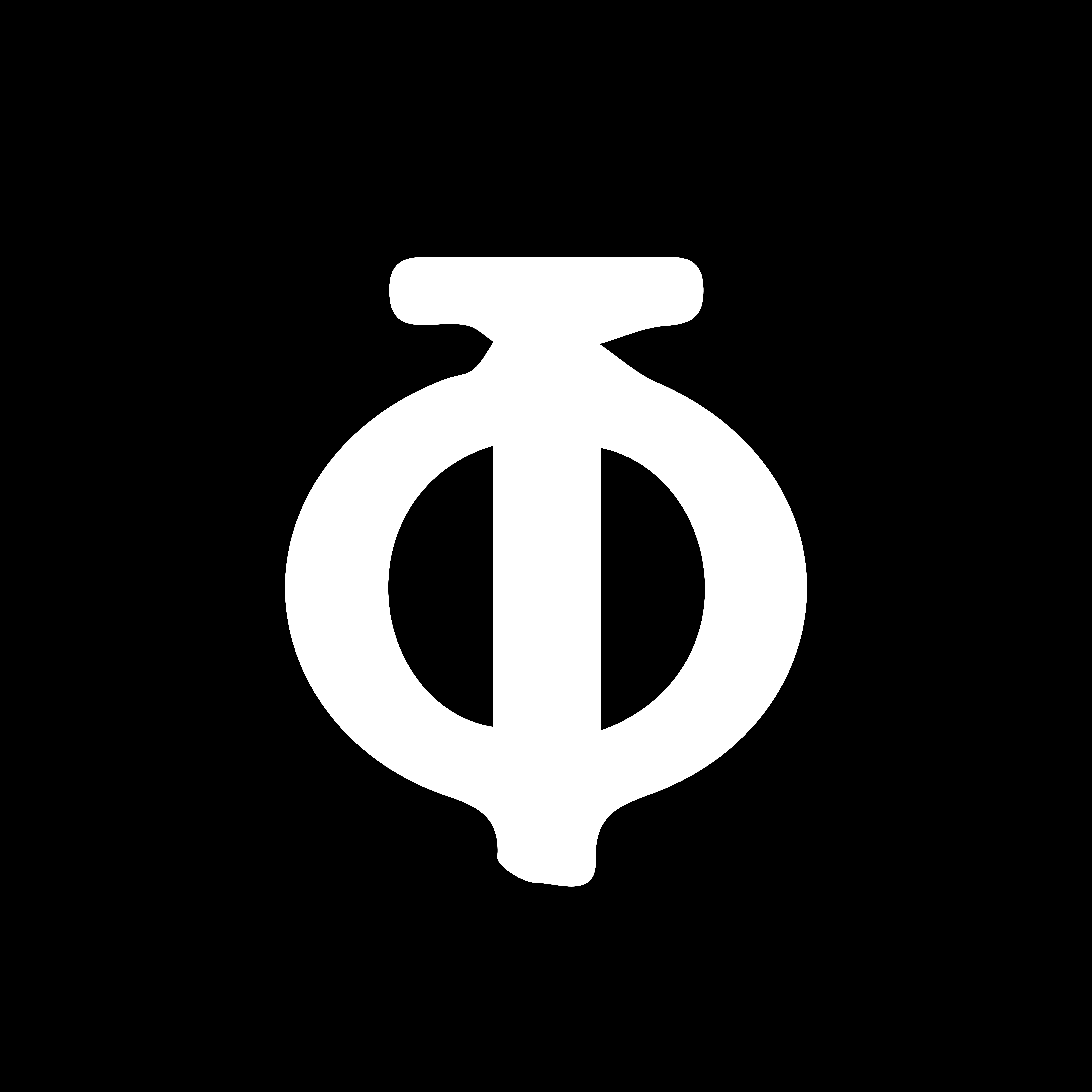



Comments