Catatan Dari Pabrik Seni
- Priyo Utomo Laksono
- 1 day ago
- 4 min read

Esai pengantar kunjungan lapangan
Siang itu Majalengka terasa seperti jeda panjang. Panas dan lembab, bukan jenis panas yang heroik, melainkan panas yang membuat keringat mengendap di lipatan punggung dan pikiran berjalan sedikit lebih lambat. Jalanan kabupaten mulus—terlalu mulus— sibuk standar kabupaten dan tanpa angkutan publik. Sebuah kota yang fungsional tapi renggang, seperti kalimat yang benar secara tata bahasa namun kehilangan musiknya.
Di sisi sebuah pabrik seni genteng di Jatiwangi, di beranda samping yang setengah terbuka, saya bertemu dengan Arif Yudi, seniman Majalengka.
Sebagian bangunan pabrik itu kini berubah fungsi. Dapur MBG—sebuah proyek pusat dari Jakarta—mengambil ruang yang dulunya bagian dari ekosistem kerja Jatiwangi Art Factory. Kehadiran “Capitol” di distrik, lagi-lagi. Negara hadir sebagai program, sebagai logistik, sebagai dapur; sementara seni—seperti biasa—mencari celah di pinggir. Setelah menghindari bising kelontang dan desah kompor dapur umum, Arif menyambut saya dan rekan fotografer saya dari samping sebuah dispenser, mengajak saya ke bagian lain area itu. Dia meminta izin untuk menemani sembari mengerjakan sesuatu. Kami duduk di bengkel terbuka di samping Gedung. Tidak ada studio putih. Tidak ada aura kuratorial. Hanya lantai berdebu terakota, meja kerja seadanya, dan jajaran rak berisi jajaran tangan dan kaki yang begitu nyata namun terbuat dari terakota.
Arif Yudi adalah pria paruh baya dengan rambut pendek setengah beruban. Kacamata bulat kecil berbingkai hitam, kaos hitam generik yang sudah lama berdamai dengan debu dan tanah liat. Bicaranya tenang, cenderung lembut, tapi di sela-selanya sesekali muncul humor yang cerkas—jenis humor yang biasanya dimiliki orang-orang yang pikirannya bekerja lebih cepat dari mulutnya. Indikator bahwa ini bukan kesederhanaan kosong, melainkan kerumitan yang memilih diam.
Di sampingnya ada Subita. Pria paruh baya dengan rambut hitam legam, keriting, berkacamata bingkai kotak tebal. Tangannya—urat-uratnya menonjol—adalah tangan pengrajin tulen, tangan yang mengenal tekanan, berat, dan kegagalan material. Mereka bekerja di samping pabrik seni/genteng itu, bukan di ruang terpisah. Tidak ada jarak simbolik antara produksi dan refleksi. Seni dan kerja berdampingan tanpa perlu dipisahkan oleh bahasa institusional.
Jatiwangi Art Factory—JAF—berdiri hampir dua dekade lalu sebagai respon yang nyaris tak masuk akal tapi justru sangat Indonesia: sebuah pabrik seni di daerah buruh genteng, dengan material utama tanah yang sama dengan genteng itu sendiri. “Banyak seniman di Bandung juga mengerjakan material yang sama,” kata Arif, datar. Dan tentu saja benar. Tapi bagi saya, perbedaannya bukan pada material, melainkan pada tempat dan kelas yang melahirkannya.
Bahwa inisiatif ini lahir dari Jatiwangi—bukan dari kota seni, bukan dari kampus seni, bukan dari pusat kebudayaan—adalah fakta puitis. Sebuah kepekaan yang tumbuh dari kultur produksi, bukan dari jarak aman galeri. Ini adalah inisiatif kelas pekerja tanpa perlu membawa spanduk ideologi. Working class initiative, tanpa harus berbau Marxis. Meski kita tahu, di masa Orde Baru, kepekaan semacam ini mungkin akan dengan mudah dihantam label “kiri”—sebuah label yang seringkali lebih malas daripada analitis.
Saat itu Arif dan Subita sedang mengerjakan tangan dan kaki dari terakota—material genteng yang dimuliakan tanpa disucikan. Realismenya mencengangkan. Otot, urat, lipatan kulit—semuanya hadir dengan ketelitian yang membuat saya terdiam lebih lama dari yang saya rencanakan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi sekaligus sangat purba dalam bentuk-bentuk itu. Seperti melihat ulang tangan Adam dan Hawa saat pertama kali Tuhan—atau para dewa Olimpus, atau dewa-dewa Mahameru—mencoba memahami apa artinya menciptakan manusia.
Saya bertanya soal presisi. Soal ukuran nadi, otot, proporsi. Apakah itu dipelajari secara formal?
“Iya,” jawab Subita singkat.
Lalu ia menambahkan sesuatu yang menggeser percakapan kami ke wilayah yang lebih berbahaya—dan lebih menarik. “Yang paling sulit itu wajah.”
Wajah, katanya, sering gagal. Secara teknis terlihat mudah. Secara visual tampak bisa direplikasi. Tapi hampir selalu meleset. Tidak mirip. Ada yang hilang. Ada yang tidak mau hadir.
Saya menanggapi, mungkin agak terlalu refleks: sepertinya wajah mengandung dimensi gaib.
Dalam arti yang sederhana tapi serius: wajah adalah medan psikologis. Tempat ekspresi dan kejiwaan saling tumpang tindih. Wajah adalah jendela jiwa—klise, ya, tapi klise sering bertahan karena memuat kebenaran yang sulit digantikan. Kerumitan wujud manusia terangkum di sana. Tubuh bisa direduksi ke anatomi; wajah menolak.
Percakapan itu terasa absurd dan agung sekaligus. Seolah kami sedang bermain peran sebagai dewa-dewa setengah pensiun, membahas kegagalan dan keberhasilan penciptaan manusia di siang Majalengka yang pengap. Tidak ada dupa. Tidak ada altar. Hanya tanah, keringat, dan humor ringan yang sesekali menyelamatkan kami dari keseriusan berlebihan.
Di titik ini saya teringat masa kuliah, pada satu kelas Filsafat Yunani ketika dosen saya bercerita tentang peradaban Helenistik. Tentang air mancur—fountain—yang pada mulanya bukanlah objek estetika, melainkan indikator. Tanda bahwa urusan teknis pengairan dan sanitasi kota telah selesai. Keindahan hadir sebagai excess, sebagai efek samping dari penyelesaian masalah teknis.
JAF bekerja dengan logika serupa, tapi dari arah yang lebih jujur. Ia tidak menunggu masalah selesai. Ia hadir di tengah produksi, di tengah rutinitas, di tengah potensi banalitas kerja. Seni di sini bukan kemewahan pasca-kemakmuran, melainkan strategi bertahan hidup secara kultural. Sebuah cara menyelamatkan manusia dari menjadi sekadar perpanjangan alat produksi.
Dan ini penting dalam konteks Indonesia hari ini.
Media Distrik Utara—tempat permenungan ini bernaung—secara terang mengarahkan perhatian pada gerakan distrik dan daerah dalam pembangunan. Sebuah posisi yang, menurut saya, bukan hanya relevan tapi mendesak. Pembangunan nasional kita terlalu lama bertumpu pada imajinasi pusat. Jakarta masih menyedot porsi ekonomi yang tidak proporsional, sementara daerah—distrik—sering diposisikan sebagai penonton yang diminta bersabar.
Jatiwangi menawarkan agensi lain. Agensi kelas pekerja. Bukan sebagai perlawanan frontal terhadap pusat, melainkan sebagai pernyataan keberadaan: kami berpikir, kami mencipta, kami punya bahasa sendiri.
Ironisnya, di hari saya bertemu Arif, sebagian ruang JAF digunakan untuk dapur proyek pusat. Sebuah ironi yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Seni berdampingan dengan logistik negara. Tanah yang sama, fungsi yang berbeda. Di satu sisi, negara hadir dengan niat baik dan skala besar. Di sisi lain, distrik mempertahankan ruang kecil untuk berpikir, meraba, dan gagal.
Mungkin memang seperti itu nasib daerah produksi: selalu berdampingan dengan kekuatan yang lebih besar, tapi tidak harus kehilangan suaranya.
Ada sesuatu yang penting dalam pengalaman ini: duduk di tempat yang bukan destinasi, berbincang dengan orang-orang yang tidak sedang menjual narasi heroik, mendengarkan cerita tentang kerja, mimpi dan humor kecil yang muncul di sela debu. Makna sering bersembunyi di bengkel, di dapur, di ruang kerja samping—bukan di podium atau presentasi kebijakan.
Jatiwangi Art Factory adalah ruang semacam itu. Sebuah tempat di mana seni tidak mengklaim menyelamatkan dunia, tapi mungkin—perlahan—menyelamatkan manusia dari kehampaan rutinitas.
Ketika saya pamit, panas belum berkurang. Jalanan Majalengka tetap . Tapi saya pulang dengan perasaan bahwa di distrik seperti Jatiwangi, ada sesuatu yang sedang dijaga dengan serius: martabat kerja, kerumitan rasa, dan keberanian untuk membayangkan keindahan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai efek samping dari keberanian untuk peka.
Dan mungkin, di negara yang terlalu lama memuja pusat, kepekaan semacam itu adalah bentuk pembangunan yang paling sunyi—dan paling radikal.
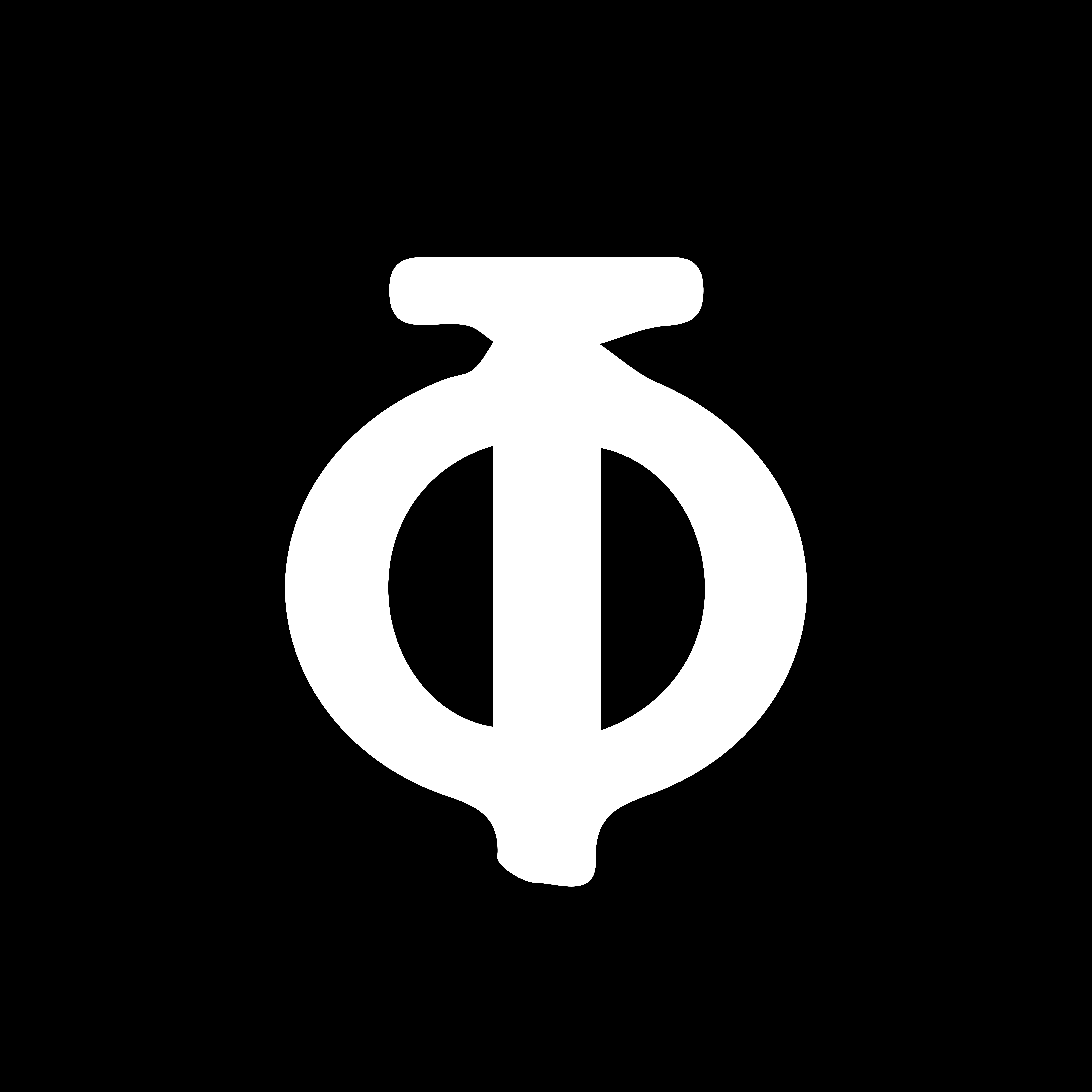



Comments