Dialektika Abadi Pusat dan Daerah
- Priyo Utomo Laksono
- 6 days ago
- 3 min read
Updated: 3 days ago

Diskusi Indra Hidayat (pengusaha, konsultan, lulusan Teknik Mesin ITB), Arif Yudi (seniman, pendiri Jatiwangi Art Factory), dan Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D. (dosen ITB) di Video Podcast Distrik Utara
Presiden Snow sudah tua.
Dalam The Hunger Games, tubuhnya rapuh, napasnya pendek, tangannya sering bergetar. Tapi kekuasaan justru semakin terkonsentrasi. Ia tidak berteriak. Ia tidak perlu. Segalanya berjalan karena sistem sudah mapan—karena distrik-distrik telah lama belajar patuh. Ketimpangan tidak lagi dipaksakan setiap hari; ia cukup dirawat, dipelihara, diwariskan.
Saya selalu merasa bagian paling mengganggu dari dunia Panem bukanlah kekerasannya, melainkan keteraturannya. Sebuah ketimpangan yang sudah menjadi kebiasaan. Distrik-distrik tahu posisinya. Capitol tahu porsinya. Semua bergerak di dalam logika yang sama, seolah-olah tidak ada alternatif.
Renungan ini muncul setelah saya menyimak sebuah perbincangan panjang dalam podcast Distrik Utara—sebuah diskusi yang melibatkan Indra Hidayat (pengusaha, konsultan, lulusan Teknik Mesin ITB), Arif Yudi (seniman, pendiri Jatiwangi Art Factory), dan Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D. (dosen ITB). Obrolan mereka tidak sedang mencari kesimpulan. Ia lebih seperti membuka lapisan-lapisan lama yang selama ini kita anggap wajar: relasi pusat dan daerah.
Relasi ini, jika kita jujur, bukan barang baru. Jauh sebelum republik, bahkan sebelum kolonialisme, kita sudah mengenalnya. Majapahit—dan barangkali Sriwijaya—sudah mempraktikkan logika pusat dan pinggiran. Ada mandala, ada wilayah taklukan, ada upeti, ada pengaturan aliran sumber daya. Sentralisasi bukan anomali; ia bagian dari sejarah panjang kekuasaan di Nusantara.
Namun kolonialisme Belanda mengubah skalanya secara drastis. Sentralisasi tidak lagi sekadar alat politik, melainkan mesin ekonomi. Kolonialisme adalah manifestasi langsung dari Revolusi Industri: kebutuhan bahan mentah, efisiensi logistik, standarisasi administrasi. Daerah direduksi menjadi pemasok—gula, kopi, karet, timah—sementara pusat (Batavia, lalu Amsterdam) menjadi pengendali nilai tambah. Pola ini bukan sekadar praktik, tapi blueprint. Dan cetak biru itulah yang, sadar atau tidak, masih kita rasakan hari ini.
Dalam perbincangan itu, satu angka terus terngiang di kepala saya. Bahwa hingga hari ini, Jakarta masih menyumbang lebih dari 25% perekonomian Indonesia, sementara puluhan kota menengah dan kecil lainnya—jika digabungkan—kontribusinya bahkan tidak mencapai 20%. Angka ini saya tangkap dari penjelasan Wilmar A. Salim, dan ia terasa seperti tamparan statistik: telak, dingin, dan sulit dibantah.
Tentu, Indonesia hari ini bukan Indonesia era Soeharto. Itu harus diakui. Desentralisasi nyata terjadi. Otonomi daerah membuka ruang. Infrastruktur menyebar. Internet mendistribusikan informasi, bahkan ilusi egalitarianisme. Anak di Wamena bisa menonton kuliah MIT. Petani di Flores bisa viral di TikTok. Ada perasaan bahwa jarak menyempit.
Namun ketika semuanya dikuantifikasi—PDRB, kualitas lingkungan, arus investasi, pengambilan keputusan strategis—pola sentralistik itu tetap muncul. Bahkan belakangan, ada kesan ia kembali menguat. Seolah negara, setelah mencicipi desentralisasi, merasa perlu menarik napas panjang dan berkata: “cukup, mari kita rapikan lagi.”
Di titik ini, saya teringat Thomas Hobbes dan Leviathannya. Negara, dalam logika Hobbesian, memang harus menjadi preman tunggal. Pemegang kekerasan absolut agar kekacauan tidak merajalela. Dalam versi Indonesia, barangkali negara memang tidak lebih—dan mungkin tidak kurang—dari itu. Pertanyaannya: sampai sejauh mana?
Apakah sentralisasi adalah harga yang harus dibayar untuk stabilitas? Apakah dialog, demokrasi, dan tarik-ulur dengan daerah mulai dianggap terlalu mahal, terlalu lambat, terlalu tidak cost-efficient di era akselerasi informasi dan industri? Jangan-jangan Yuval Noah Harari tidak sepenuhnya keliru ketika ia memperkirakan totalitarianisme akan merebak karena proses-proses di negara demokrasi menjadi terlalu mahal dalam kecepatan informasi/industry yang semakin ngebut.
Namun jika demikian, apa yang sebenarnya harus dibangun di daerah?
Pertanyaan ini lebih mengganggu daripada sekadar soal anggaran atau kewenangan. Karena ia menyentuh soal budaya. Warga daerah selama ini sering diposisikan sebagai objek pembangunan. Bahkan ketika dilibatkan, keterlibatan itu kerap bersifat prosedural. Padahal kekuatan sejati daerah bukan hanya pada sumber daya alam atau PDRB, melainkan pada kapasitas warganya untuk berdialektika.
Berdialektika, bukan memberontak. Bernegosiasi, bukan mengemis. Menyusun imajinasi kolektif, bukan sekadar menunggu instruksi.
Di sinilah saya kembali ke The Hunger Games. Distrik-distrik tidak langsung melawan. Mereka lama menerima. Sampai suatu titik, kesadaran itu tumbuh bukan karena lapar semata, melainkan karena martabat. Karena rasa bahwa mereka bukan sekadar pemasok bagi Capitol.
Indonesia belum—dan semoga tidak pernah—sampai pada titik itu. Tapi sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan yang terlalu lama dirawat akan melahirkan respon. Tidak selalu dalam bentuk kekerasan, tapi bisa dalam penarikan loyalitas, dalam sinisme, dalam jarak emosional terhadap pusat.
Maka cliffhanger-nya ada di sini:
budaya apa yang perlu disemai di “distrik-distrik” Indonesia agar mereka mampu berdialektika dengan pusat, tanpa harus menjadi Panem?
Bukan budaya ketergantungan. Bukan pula romantisme kedaerahan sempit. Mungkin budaya percaya diri kolektif. Budaya literasi kebijakan. Budaya seni yang politis tapi tidak partisan. Budaya wargaan yang sadar bahwa negara bukan dewa, tapi juga bukan musuh.
Saya tidak punya jawabannya. Dan esai ini memang tidak berniat menutup apa pun. Ia hanyalah catatan pinggir—renungan setelah mendengar tiga orang berbincang, membuka peta lama, dan menyadari bahwa relasi pusat dan daerah di Indonesia adalah dialektika abadi. Ia bergerak, berulang, berubah bentuk, tapi tak pernah benar-benar selesai.
Seperti Presiden Snow yang menua: tubuh kekuasaan bisa rapuh, tapi sistemnya sering justru semakin rapi. Pertanyaannya selalu sama—dan akan terus sama:siapa yang merawat sistem itu, dan untuk siapa?
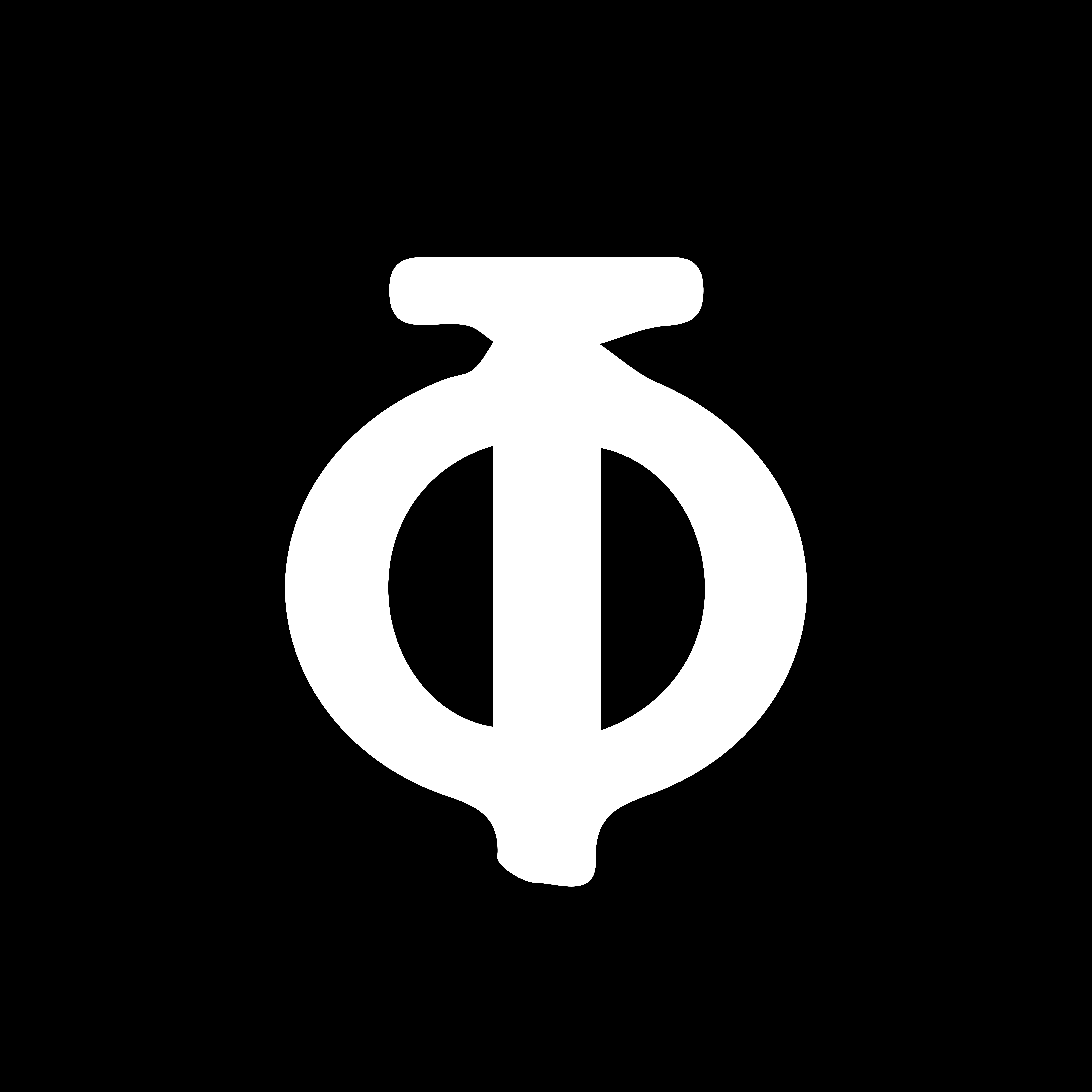



Comments