Catatan dari Tanah Basah
- Priyo Utomo Laksono
- 6 days ago
- 4 min read
Updated: 3 days ago

Dokumentasi acara Rampak Genteng di Dusun Bambu
Catatan dari Pameran Material Connex: Jatiwangi Art Factory di Dusun Bambu
Hujan turun deras hari itu. Bukan hujan yang romantis dan sopan, tapi hujan Bandung yang jatuh seperti sedang menguji kesabaran: rapat, dingin, dan tak memberi jeda. Hujan jenis yang belakangan ini semakin sering kita jumpai—hujan ekstrem, hujan yang datang terlalu cepat, terlalu lama, atau terlalu banyak. Dusun Bambu basah dari ujung ke ujung—tanah licin, pepohonan menggelap, suara air jatuh bertubrukan dengan bambu, genteng, dan napas para pengunjung yang menyesuaikan langkah.
Saya datang bersama anak-anak saya, dengan rencana sederhana: melihat pameran seni. Tapi seni, seperti cuaca dan seperti hidup, sering kali punya rencana lain.
Di Dusun Bambu, sejak 14 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026, Material Connex berlangsung—sebuah pameran seni yang mempertemukan material, proses, dan cerita, hasil kolaborasi Dusun Bambu dengan Jatiwangi Art Factory (JaF). Fokusnya bukan sekadar objek seni, melainkan relasi: antara manusia dan tanah, antara kebudayaan dan bahan, antara yang diproduksi dan yang diwariskan—di tengah dunia yang kian sering berhadapan dengan krisis ekologis, banjir, longsor, dan cuaca yang tak lagi bisa diprediksi dengan tenang.
Dan hari itu, relasi itu terasa literal. Semua karya yang tersebar di seantero wahana terbuat dari tanah liat bakar—terracotta, genteng—material yang dalam keseharian kita berfungsi paling dasar sebagai pelindung dari hujan. Sementara hujan, pada hari itu, sedang bekerja keras membuktikan dirinya.
Saya berjalan sambil menghindari genangan, melewati instalasi miniatur kerbau yang beriring, rusa-rusa kutub dari tanah, puluhan lonceng (bells) yang menggantung di pepohonan, gnome Sunda, piramida kecil, totem lingga—semuanya sunyi, basah, dan bersabar. Seolah karya-karya itu tidak sedang dipamerkan, melainkan dikembalikan ke habitat asalnya: alam, cuaca, dan siklus waktu.
Terracotta selalu punya watak paradoks. Ia lahir dari tanah, dibentuk oleh tangan, lalu dikeraskan oleh api—namun tetap rapuh. Ia melindungi rumah dari hujan, tapi akan pecah jika jatuh. Ia adalah simbol peradaban sekaligus pengingat keterbatasannya. Dalam dunia yang terobsesi pada material sintetis dan sekali pakai, tanah liat justru mengingatkan kita pada sesuatu yang bisa kembali ke tanah, terurai, dan memulai siklus baru.
Dan mungkin itu sebabnya pameran ini terasa tepat berada di ruang terbuka, bukan di white cube galeri. Material Connex tidak sedang memamerkan seni sebagai “objek”, tapi sebagai hubungan ekologis—sebagaimana tertulis dalam pengantarnya: interkoneksi antara material, makna, dan konteks lokal, di tengah krisis lingkungan yang tidak lagi bisa dianggap isu masa depan.
Krisis itu terasa nyata saat hujan tidak kunjung reda. Kita hidup di masa ketika hujan bukan sekadar fenomena alam, tapi juga indikator ketidakseimbangan: tata ruang yang abai, material yang menutup tanah, sungai yang dipersempit, dan hubungan manusia dengan bumi yang semakin transaksional.
Lalu datanglah momen yang mengubah semuanya dari sekadar pameran menjadi pengalaman: Rampak Genteng.
Di satu titik, para seniman JaF mengajak pengunjung—termasuk anak-anak saya—untuk ikut serta dalam konser perkusi menggunakan genteng. Tidak ada jarak antara performer dan penonton. Tidak ada panggung tinggi. Hanya tanah basah, tangan dingin, dan bunyi genteng yang ditabuh bersama.
Anak-anak tertawa, orang dewasa kikuk, lalu larut. Genteng—yang biasanya diam di atap, yang fungsinya melindungi dan tak bersuara—hari itu berbunyi. Bukan bunyi yang rapi, bukan komposisi simfonik. Tapi bunyi kolektif, mentah, dan jujur. Bunyi material yang selama ini hanya kita ingat saat bocor atau pecah.
Saya menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting: ini bukan seni partisipatif sebagai gimmick, tapi sebagai pengembalian fungsi sosial material. Genteng kembali menjadi milik bersama. Tanah kembali menjadi ritme. Material kembali punya suara.
JaF memang tidak pernah memisahkan praktik seni dari praktik hidup. Berbasis di Jatiwangi—wilayah yang sejarah industrinya sangat lekat dengan genteng dan tanah liat—mereka bekerja di persimpangan arsip, komunitas, dan eksperimen. Genteng bukan simbol yang dicari-cari; ia adalah realitas sehari-hari yang diangkat kembali ke ruang refleksi, sekaligus kritik halus terhadap budaya material modern yang sering lupa pada asal-usulnya.
Dalam konteks Material Connex, genteng dipertemukan dengan bambu, material yang menjadi identitas Dusun Bambu. Keduanya sama-sama material lokal, sama-sama lahir dari kerja kolektif, sama-sama dapat diperbarui dan didaur ulang, dan sama-sama sering dianggap remeh. Namun di tangan JaF, banalitas itu justru dibongkar: bagaimana material membentuk cara kita hidup, bekerja, berlindung, dan membayangkan keberlanjutan.
Hujan membuat semua ini terasa lebih tajam. Tanah basah mengeluarkan aroma yang akrab. Genteng licin mengingatkan fungsi aslinya. Anak-anak yang menabuh genteng seolah sedang belajar, tanpa ceramah, tentang asal-usul rumah, tentang dari mana perlindungan datang, dan tentang hubungan antara manusia dan bumi yang tidak sepenuhnya bisa diputus.
Saya memikirkan satu hal: mungkin seni yang paling relevan hari ini bukan yang paling canggih, tapi yang paling dekat dengan material asal peradaban. Tanah. Api. Air. Tangan. Dalam banyak tradisi—termasuk kisah penciptaan manusia pertama—kita diingatkan bahwa manusia berasal dari tanah. Adam dibentuk dari lempung. Bukan dari baja, bukan dari plastik, bukan dari beton.
Mungkin kita lupa itu terlalu lama.
Di tengah berbagai krisis—ekologi, pangan, makna—Material Connex terasa seperti pengingat pelan tapi keras: bahwa kita terlalu lama memutus hubungan dengan bahan dasar hidup kita. Kita mengonsumsi tanpa menyentuh, membangun tanpa memahami, berlindung tanpa menyadari dari apa perlindungan itu dibuat, dan membuang tanpa berpikir ke mana material itu akan kembali.
JaF tidak menawarkan solusi. Mereka menawarkan pengalaman menyadari kembali—bahwa tanah bukan sekadar sumber daya, melainkan asal dan tujuan.
Saat hujan mulai reda, saya melihat kembali lonceng-lonceng tanah yang tergantung di pepohonan. Beberapa berbunyi tertiup angin. Tidak nyaring. Hampir seperti bisikan. Seolah tanah sedang berbicara pelan—tentang kerja, tentang waktu, tentang kesabaran, dan tentang kemungkinan untuk hidup lebih selaras.
Anak-anak saya basah, kedinginan, dan bahagia. Saya juga. Kami pulang dengan sepatu kotor dan kepala penuh bunyi genteng.
Dan saya tahu, ini bukan kunjungan terakhir. Karena seni yang baik, seperti genteng yang baik, tidak mengkilap—tapi bertahan saat hujan datang, dan tahu ke mana ia harus kembali ketika segalanya usai.
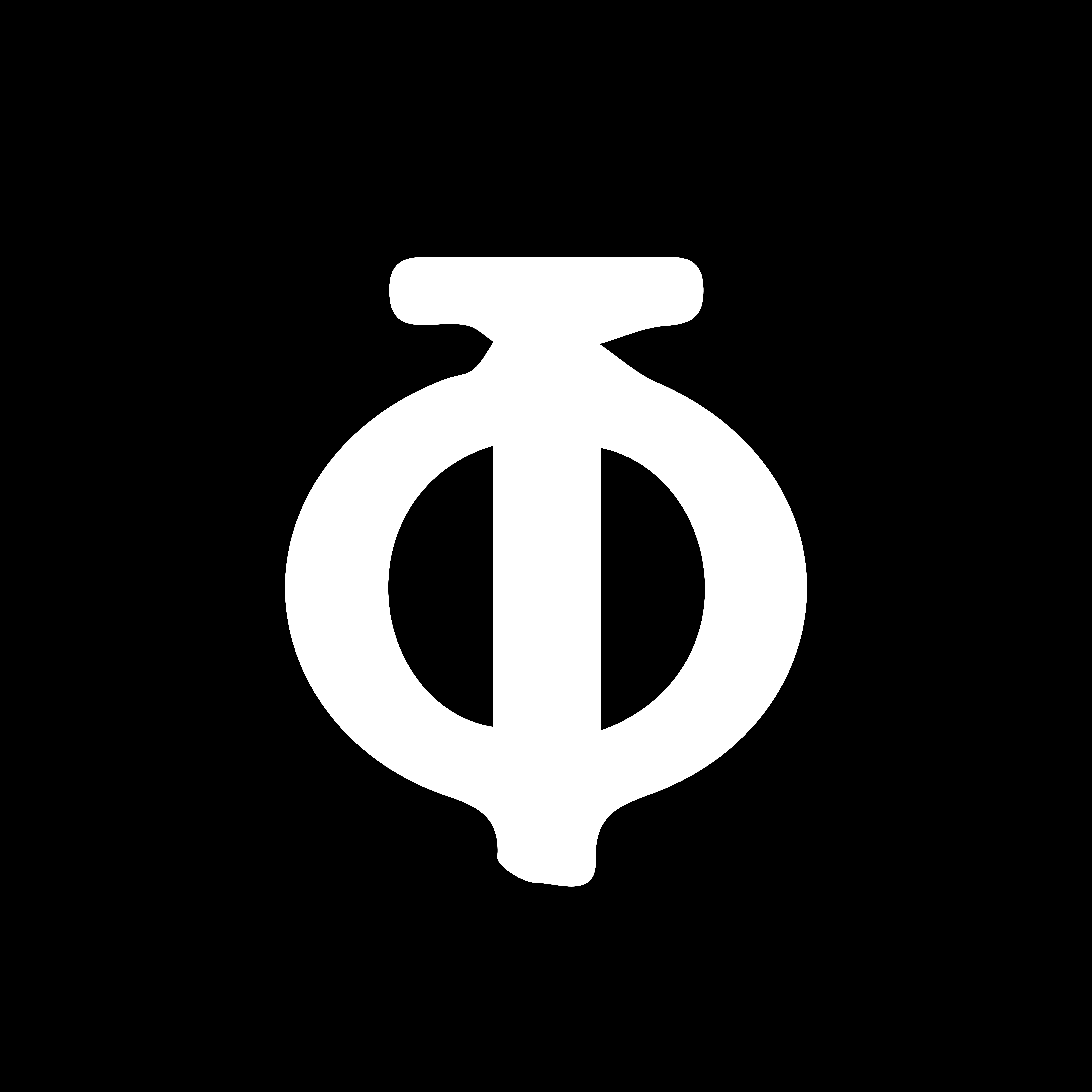



Comments