Bencana, Bahasa, dan Jarak yang Tidak Pernah Masuk Peta
- Priyo Utomo Laksono
- Dec 18, 2025
- 4 min read
Updated: Dec 19, 2025

Setiap kali bencana datang, kita seperti sedang menonton film yang pernah kita tonton, tapi tetap berharap ending-nya berubah. Air naik, rumah terendam, kamera televisi mencari sudut paling dramatis, lalu kita semua—termasuk saya—ikut mengangguk serius di depan layar.
Kita teringat satu adegan dalam film Parasite. Hujan deras yang bagi keluarga kaya hanyalah gangguan kecil—alasan untuk mengeluh soal bau lembap—adalah kiamat kecil bagi keluarga miskin yang tinggal di semi-basement. Air yang sama. Hujan yang sama. Dampak yang sama sekali tidak setara.
Di Indonesia, kita tidak perlu fiksi untuk menggambarkan itu. Beberapa minggu terakhir, Sumatra kembali kebanjiran. Bukan satu titik, tapi berlapis-lapis: Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan. Data BNPB mencatat bahwa sebagian besar bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi—banjir, longsor, cuaca ekstrem—dan hampir semuanya berulang di tempat yang sama. Jika ini sebuah film, penonton pasti sudah keluar bioskop sambil mengomel: “Kok ceritanya muter di situ-situ aja?”
Masalahnya, ini bukan film. Dan kita tidak punya kemewahan untuk berhenti menonton.
Bencana sebagai Pembuka Paksa
Bencana punya satu sifat yang tidak dimiliki pidato pejabat atau laporan kebijakan: ia jujur. Ia tidak peduli dengan narasi pembangunan, visi jangka panjang, atau jargon teknokratik. Ia datang, lalu membuka apa yang selama ini kita pura-pura tidak lihat.
Yang terlihat bukan hanya rumah roboh atau jalan terputus, tapi struktur sosial yang ikut retak. Siapa yang paling dulu terdampak. Siapa yang paling lama pulih. Siapa yang sejak awal memang tidak punya bantalan apa-apa.
Namun setelah fase darurat lewat, kita cenderung kembali ke kebiasaan lama: membicarakan solusi di ruang-ruang yang sunyi dari suara warga. Di sinilah persoalan lain muncul—yang jauh lebih halus, tapi dampaknya panjang.
Kesenjangan yang Tidak Dramatis Tapi Mematikan
Episode kedua podcast Distrik Utara berangkat dari obrolan dengan Prasanti Widyasih Sarli—Asih—dosen dan peneliti yang mengembangkan inovasi pemetaan kerentanan bangunan terhadap gempa. Awalnya, seperti yang bisa diduga, pembicaraan bergerak di wilayah teknis: risiko, struktur bangunan, data, metode.
Lalu obrolan itu bergeser. Bukan karena disengaja, tapi karena begitulah percakapan yang hidup bekerja.
Yang muncul bukan perdebatan soal benar atau salah, melainkan satu problem klasik yang jarang dibicarakan secara terbuka: kesenjangan komunikasi antara masyarakat akar rumput dan kalangan peneliti atau intelektual.
Ini bukan soal siapa lebih pintar. Ini soal siapa berbicara dengan bahasa siapa.
Bahasa yang Tidak Pernah Sampai
Di satu sisi, kita punya dunia akademik yang bekerja dengan ketelitian tinggi, kehati-hatian metodologis, dan istilah-istilah yang presisi. Di sisi lain, kita punya masyarakat yang hidup dengan pertanyaan sederhana dan sangat praktis:
“Kalau rumah saya rawan, saya harus ngapain besok pagi?”
“Kalau disuruh pindah, saya kerja di mana?”
“Kalau bangunan saya tidak sesuai standar, siapa yang bantu?”
Sering kali, dua dunia ini tidak bertabrakan—mereka bahkan tidak saling bersentuhan. Pengetahuan bergerak ke atas, laporan naik ke rak, jurnal terbit. Sementara di bawah, masyarakat bertahan dengan logika yang sama sekali berbeda: logika bertahan hidup.
Akibatnya, lahir situasi absurd yang sudah kita normalisasi:
solusi ada, tapi tidak dipahami.
data tersedia, tapi tidak dipercaya.
rekomendasi dibuat, tapi tidak dijalankan.
Bukan karena masyarakat anti-ilmu. Bukan karena peneliti tidak peduli. Tapi karena tidak ada bahasa bersama.
Intelektual dan Masyarakat: Dua Arah yang Jarang Ditempuh
Ada anggapan diam-diam bahwa tugas intelektual adalah “mengedukasi masyarakat”. Kalimat ini terdengar mulia, tapi sering kali berangkat dari asumsi satu arah: yang satu tahu, yang lain tidak.
Padahal, masyarakat akar rumput bukan ruang kosong yang menunggu diisi. Mereka punya pengetahuan kontekstual yang tidak pernah masuk jurnal: tentang pola air, tentang bangunan mana yang selalu retak duluan, tentang kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman berulang.
Masalahnya, pengetahuan ini jarang naik ke atas. Tidak terdokumentasi. Tidak terjemahkan. Tidak dianggap “data”.
Di titik ini, kita perlu jujur: banyak percakapan tentang mitigasi bencana gagal bukan karena kurang canggih, tapi karena terlalu cepat merasa sudah cukup pintar.
Distrik Utara dan Percakapan yang Tidak Rapi
Sebagai redaktur Distrik Utara, saya tidak tertarik menjadikan podcast ini sebagai ruang kesimpulan. Kami tidak sedang mencari satu jawaban yang bisa dipajang sebagai solusi final.
Yang kami coba lakukan—dengan segala keterbatasan—adalah membuka percakapan yang selama ini canggung. Percakapan yang tidak rapi. Kadang melantur. Kadang tidak nyaman. Tapi justru di situlah nilai manusianya.
Episode ini bukan tentang apa yang Asih yakini atau tidak yakini. Ia tentang ruang temu: antara riset dan realitas, antara peta dan pengalaman, antara bahasa akademik dan bahasa dapur.
Jika ada satu benang merah yang bisa ditarik, mungkin ini:
mitigasi bencana bukan hanya soal teknologi, tapi soal relasi.
. Catatan Penutup (yang Sengaja Tidak Menyimpulkan)
Bencana akan terus datang. Di Sumatra hari ini, di tempat lain besok. Kita tidak bisa mengontrol hujan, gempa, atau pergerakan lempeng. Tapi kita bisa memilih apakah ingin terus berbicara dalam bahasa kita masing-masing—atau mulai repot-repot menerjemahkan.
Artikel ini adalah pengantar untuk sebuah obrolan. Bukan penghakiman. Bukan manifesto.
Hanya sebuah undangan untuk mendengarkan—dengan sedikit lebih sabar, dan mungkin sedikit lebih rendah hati.
Karena kalau ada satu hal yang selalu diajarkan bencana, itu bukan tentang alam.
Melainkan tentang jarak—dan seberapa enggan kita menjembataninya sebelum semuanya keburu runtuh.
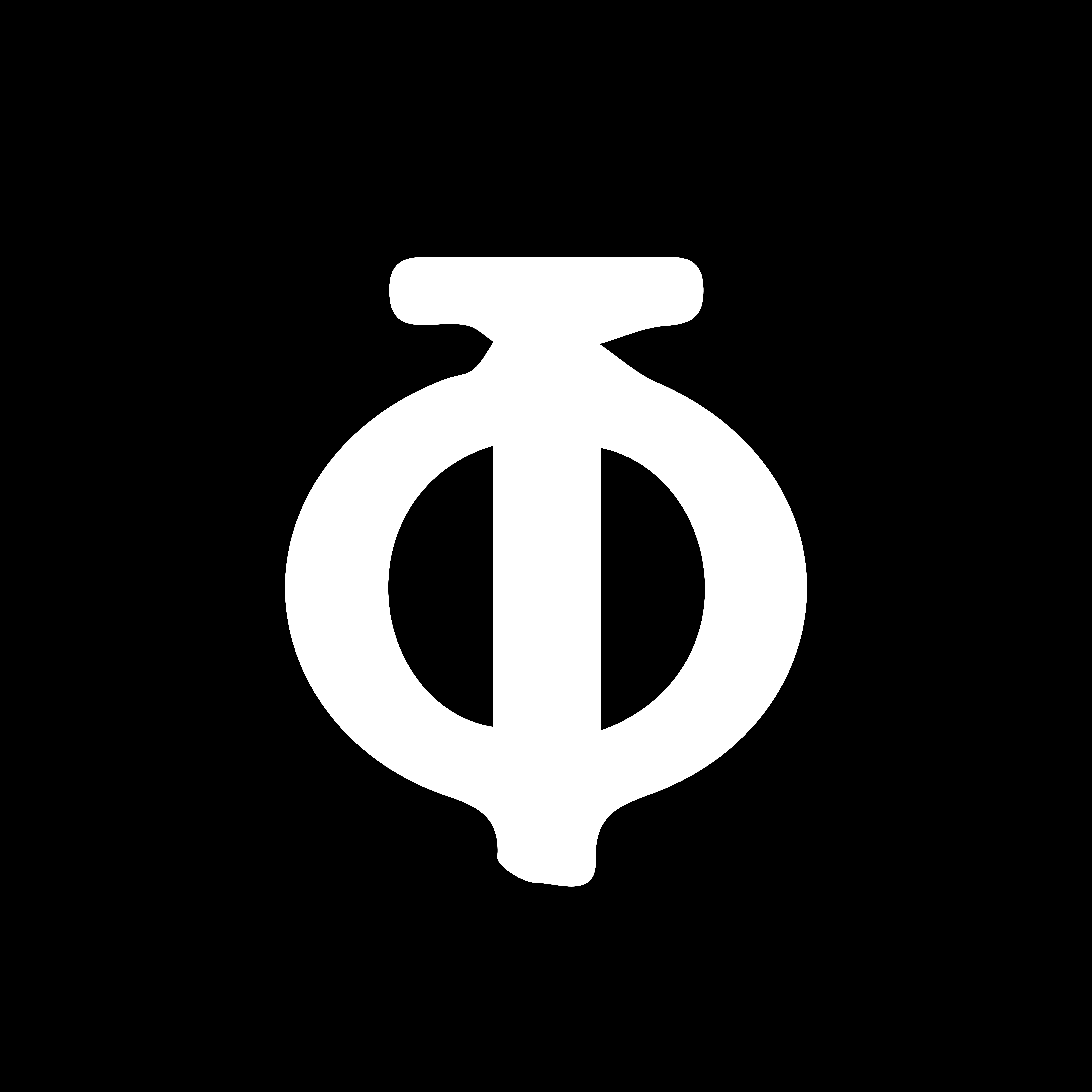



Comments