Asketisme Kuliner dalam Budaya Sunda Klasik
- Priyo Utomo Laksono
- Dec 23, 2025
- 4 min read

Ada satu kesunyian tertentu yang hanya bisa muncul setelah bunyi-bunyian yang keras. Di pendopo Temu Roti, Cigadung, kesunyian itu datang setelah anak-anak SD dari kelompok Cempaka Muda mendemonstrasikan Seni Reak Kombinasi: suara kendang yang menghentak, topeng, tubuh-tubuh kecil yang menari dengan kesungguhan yang nyaris terlalu dewasa untuk usia mereka. Lalu disusul wayang golek—yang, harus saya akui dengan dosa kultural yang sama besarnya, tidak sepenuhnya saya pahami. Tapi mungkin memang tidak semua hal perlu dipahami secara utuh untuk bisa dirasakan.
Acara sore itu adalah peluncuran buku Tutungkusan, karya Dr. Riadi Darwis—Kang Darwis—dosen di Politeknik Pariwisata NHI Bandung sekaligus pakar gastronomi, yang selama bertahun-tahun mengarsipkan ragam lalap dan rujak dari berbagai wilayah dalam lingkup peradaban Sunda. Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), beliau lebih banyak mengampu perkuliahan, tetapi kerja hidup intelektualnya justru terasa berakar pada satu hal yang sangat membumi: makanan, tumbuhan, dan ingatan kolektif yang nyaris luput dicatat.
Sebuah kerja yang, jika diukur dengan standar zaman sekarang, nyaris absurd: tebal, lambat, tidak viral, dan sangat tidak tergesa-gesa.
Saya lahir dan besar di Bandung, tetapi tumbuh dalam dominasi kebudayaan keluarga Jogja–Solo. Itu mungkin alasan yang nyaman untuk mengakui bahwa sepanjang hidup saya tidak pernah benar-benar tertarik pada kebudayaan Sunda. Lalap dan rujak bagi saya hanyalah “pendamping nasi”, bukan pintu masuk peradaban. Sampai sore itu.
Yang tiba-tiba terasa menghantam bukan sekadar ragam daun, umbi, buah, dan sambal yang dibicarakan Kang Darwis, melainkan satu kesan yang sulit dihindari: jarang sekali kebudayaan di Nusantara—atau bahkan di dunia—yang memiliki keragaman makanan sebesar itu, tetapi dengan tingkat pemrosesan serendah itu.
Lalap dan rujak Sunda, dalam pengertian paling literal, adalah makanan yang menolak diolah berlebihan. Dipetik, dicuci, diracik, dimakan. Hampir tanpa api. Hampir tanpa mesin. Hampir tanpa jarak.
Di masa kini, ketika ilmu gizi modern mulai kembali—dengan wajah baru dan istilah ilmiah—pada apa yang oleh tradisi sudah lama dipraktikkan: low processed food, seasonal diet, local sourcing, kita mendadak sadar bahwa lalap dan rujak bukan sekadar kebiasaan makan, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang utuh. Ia mensyaratkan panen musiman, kedekatan geografis, logistik jarak pendek, dan dengan sendirinya jejak karbon yang rendah.
Namun yang lebih mengganggu pikiran saya justru datang dari satu kata yang terus berputar-putar di kepala: asketisme.
Perlu sedikit kehati-hatian di sini. Yang saya maksud bukan asketisisme dalam pengertian doktrinal atau aliran spiritual yang rigid, melainkan asketisme dalam arti yang lebih literal dan kontekstual: kezuhudan, penahanan diri, dan kesadaran akan batas. Bukan pengingkaran hidup, melainkan disiplin dalam berhubungan dengan dunia material.
Asketisme biasanya diasosiasikan dengan penyangkalan diri, disiplin spiritual, atau bahkan kemiskinan yang disengaja. Dalam sejarah pemikiran, asketisme sering muncul sebagai respons terhadap kelimpahan yang berlebihan—sebuah upaya menahan hasrat agar manusia tidak tenggelam dalam dirinya sendiri. Max Weber melihat asketisme sebagai fondasi etika tertentu; Foucault membacanya sebagai teknik mengelola diri; sementara dunia modern, terutama pasar, cenderung memandangnya sebagai anomali yang tidak produktif.
Tetapi bagaimana jika lalap dan rujak Sunda adalah bentuk asketisme gastronomi?
Minimal processing bukan sekadar soal teknik memasak. Ia adalah etika. Ia membatasi sejauh mana manusia merasa berhak “mengutak-atik” alam. Dalam lalap, daun tidak dipaksa menjadi sesuatu yang lain. Ia tidak disamarkan. Ia hadir sebagai dirinya sendiri—dengan pahit, getir, getir-manis yang jujur.
Di titik ini, asketisme kuliner Sunda tampak bukan sebagai kekurangan, melainkan pengetahuan tentang batas.
Menariknya, asketisme ini tidak lahir dari larangan moral yang keras, melainkan dari keseharian. Ia tidak berkhotbah. Ia tidak menggurui. Ia hanya hadir sebagai kebiasaan yang masuk akal dalam konteks ekologisnya. Dan justru di situlah radikalitasnya.
Dalam diskusi sore itu, Kang Darwis juga bercerita tentang metode penelitiannya—yang, bagi telinga akademik modern, mungkin terdengar problematis, bahkan mistik. Ia berbicara tentang membersihkan batin, tentang puasa, tentang olah rasa, tentang menahan diri agar bisa “mendapatkan arahan” atau “inspirasi” dari para leluhur yang mewariskan tradisi ini. Saya tidak dalam posisi untuk menilai atau menghakimi metode tersebut. Tapi ada satu hal yang sulit diabaikan: bahwa proses pengetahuan di sini menuntut asketisme ganda—pada tubuh dan pada ego peneliti.
Di zaman ketika riset sering didorong oleh tenggat, dana, dan tuntutan output, asketisme semacam ini terasa hampir subversif. Ia menolak kecepatan. Ia menolak ekstraksi pengetahuan secara serampangan. Ia menuntut kesabaran, bahkan kerendahan hati.
Dan di sinilah tesis itu mulai mengeras: asketisme—baik kuliner maupun intelektual—mungkin bukan sisa masa lalu, melainkan sesuatu yang justru dibutuhkan oleh peradaban yang sedang berada di ambang batas.
Kita hidup di era krisis berlapis: krisis iklim, krisis nutrisi, krisis makna. Sistem pangan global yang hiper-efisien justru menghasilkan diet yang seragam, miskin serat, miskin mikrobiota, dan kaya penyakit metabolik. Ironisnya, solusi-solusi mutakhir yang ditawarkan sering kali kembali pada prinsip yang sangat tua: keberagaman pangan, makanan utuh, musiman, dan lokal.
Saya teringat ketika menonton dokumenter Hack Your Health: The Secrets of Your Gut bersama putra saya. Pesan pulangannya sederhana tapi mengganggu: kesehatan manusia sangat bergantung pada keragaman makanan yang kita konsumsi, terutama makanan yang minimally processed. Apa yang oleh Netflix dijelaskan dengan animasi dan grafik, oleh lalap Sunda dipraktikkan tanpa banyak kata.
Jika demikian, asketisme kuliner Sunda bukan hanya relevan secara lokal, tetapi punya implikasi universal. Ia menawarkan pelajaran tentang bagaimana peradaban bisa bertahan bukan dengan menambah, tetapi dengan mengurangi. Bukan dengan mempercepat, tetapi dengan menahan diri.
Tentu saja, asketisme adalah mimpi buruk bagi pasar. Pasar hidup dari dorongan untuk lebih: lebih cepat, lebih banyak, lebih instan. Asketisme, sebaliknya, adalah pembangkangan paling absolut terhadap logika tersebut. Ia tidak bisa di-scale up dengan mudah. Ia tidak ramah terhadap overproduksi. Ia menolak konsumsi berlebih sebagai nilai.
Mungkin karena itu asketisme sering dianggap tidak realistis. Terlalu sunyi. Terlalu lambat. Terlalu tidak menjual.
Tetapi justru di situlah kekuatannya.
Buku Tutungkusan sendiri—yang sayangnya tidak bisa saya baca karena ditulis dalam bahasa Sunda—tampak seperti simbol dari semua ini: pengetahuan yang tidak tergesa-gesa untuk dipahami semua orang, tetapi setia pada konteksnya. Sementara karya-karya Kang Darwis yang lain, setebal buku telepon dan terdiri dari beberapa jilid arsip lalap dan rujak, adalah monumen kecil terhadap sesuatu yang nyaris kita lupakan: bahwa kemajuan tidak selalu berarti menjauh dari yang sederhana.
Di pendopo itu, di antara anak-anak yang menari Reak, wayang yang asing, dan diskusi yang pelan, saya mendadak merasa bahwa kebudayaan Sunda menyimpan pelajaran yang sangat tidak Sunda-sentris. Ia bicara pada dunia yang sedang kelelahan oleh kelimpahan.
Mungkin asketisme kuliner—dan asketisme sebagai etika hidup—tidak akan menyelamatkan peradaban sendirian. Tapi ia menawarkan sesuatu yang langka: cara hidup yang tahu kapan harus berhenti. Dan di zaman ketika hampir tidak ada yang mau berhenti, itu mungkin adalah bentuk kebijaksanaan paling radikal yang tersisa.
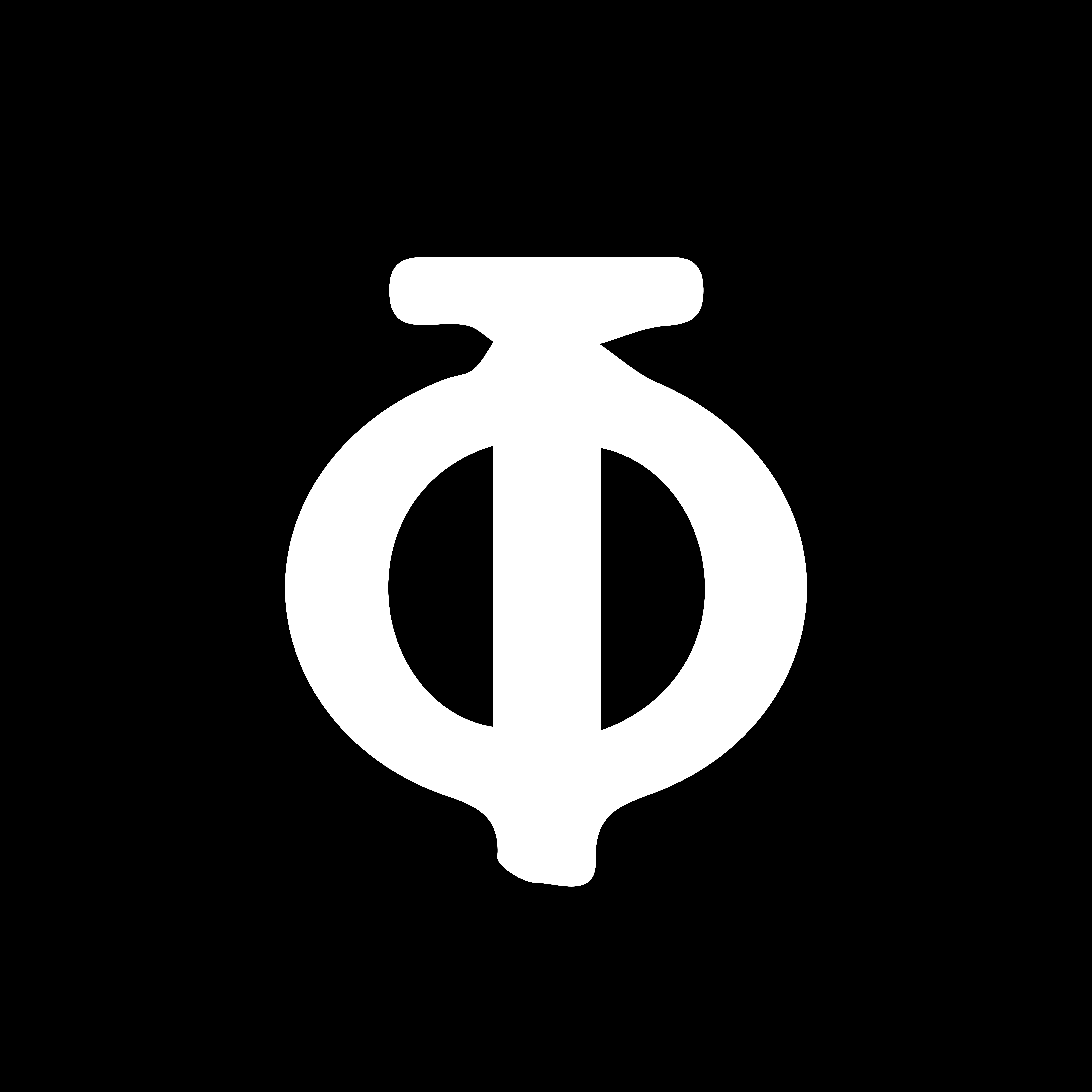



Comments